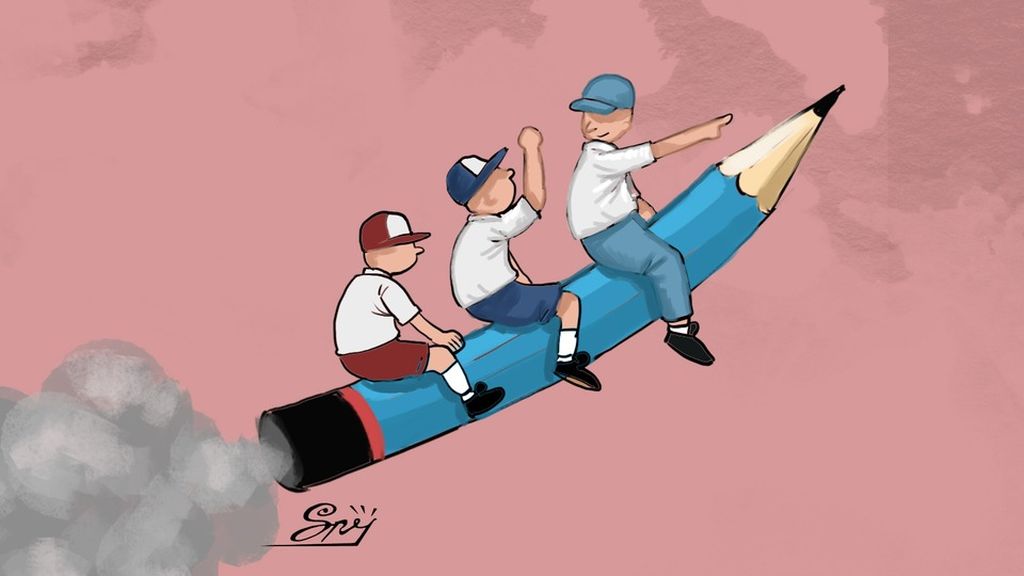Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | KURIKULUM MERDEKA: Kurikulum yang Mendewasakan |
| Tanggal | 23 Agustus 2023 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | Kurikulum Merdeka |
| AKD |
- Komisi X |
| Isi Artikel | Dunia gagasan tidak selamanya ekuivalen dengan dunia lapangan. Karena itu, perlu ada sistem evaluasi yang terus-menerus agar gagasan besar Kurikulum Merdeka benar-benar berdampak. Oleh
HERIBERTUS JANI
Gagasan tulisan ini tercetus saat membaca opini Fadhil Muhammad Pradana yang berjudul ”Mengkritik Konsepsi ’Anak sebagai Investasi Masa Depan’” (Kompas, 24/7/2023). Di antara sejumlah gugatan mengenai kekeliruan cara pandang orang dewasa terhadap anak yang mencuat dalam tulisan tersebut, penulis menangkap dua pertanyaan penting Fadhil yang perlu didiskusikan lebih jauh terutama dalam kerangka kurikulum teranyar, yakni Kurikulum Merdeka. Pertama, apakah sistem pendidikan saat ini sudah mengakomodasi keunikan dan potensi yang berbeda dari setiap anak? Kedua, sudah sejauh mana anak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan anak sendiri? Bagi mereka yang sudah menerapkan atau mengikuti dinamika Kurikulum Merdeka dari awal, minimal pada tataran konseptual, pertanyaan pertama tentu tak begitu susah dijawab. Ihwal teknis pelaksanaan pendidikan yang mengakomodasi bakat, minat, dan potensi anak untuk setiap tingkatan pendidikan sudah tertuang dalam Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Baca juga : Memerdekakan Kurikulum Merdeka Sementara pertanyaan kedua bisa diterangkan dengan memperlihatkan ruang-ruang dalam Kurikulum Merdeka yang menjadi tempat bagi anak (peserta didik) untuk menjadi subyek aktif dalam keseluruhan proses pendidikan, utamanya dalam hal pembuatan keputusan. Memang pertanyaan kedua sebenarnya merupakan gugatan untuk orang-orang dewasa yang selalu menganggap anak belum memiliki kemampuan apa-apa sehingga tidak bisa dilibatkan apalagi dibiarkan mengambil keputusan sendiri. Namun, dari arah sebaliknya perlu juga ditanyakan seberapa siap anak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Persisnya, prakondisi seperti apa yang dibutuhkan agar anak bisa merumuskan dan menyampaikan aspirasinya secara tepat? Itulah sebabnya kita perlu berbicara mengenai ruang dalam kurikulum pendidikan yang memfasilitasi anak untuk mengungkapkan gagasan dan mengambil keputusan berbasis pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pembelajaran berdiferensiasiTerlalu dini tentu untuk mengklaim bahwa Kurikulum Merdeka sudah sepenuhnya menyelenggarakan pembelajaran yang disesuaikan dengan keunikan dan potensi setiap anak. Selain karena kurikulum ini baru berjalan beberapa tahun, juga karena penerapannya masih terbatas pada sekolah-sekolah tertentu. Namun, grand design Kurikulum Merdeka sudah jelas menggariskan bahwa salah satu misi besarnya adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, setiap anak dilayani kebutuhan belajarnya sesuai potensi, bakat, dan minat yang dimiliki serta berdasarkan kecenderungan gaya belajarnya masing-masing. Untuk tujuan itu, guru, terutama guru Bimbingan dan Konseling (BK), diwajibkan membuat asesmen diagnostik, yakni proses penilaian awal untuk memetakan semua karakteristik tersebut. Mekanismenya mirip yang dilakukan dokter yang membuat diagnosis awal kepada pasien untuk memastikan tindakan apa yang tepat sesuai kondisi atau kebutuhan pasien tersebut. Konsekuensi selanjutnya, tidak ada lagi model pembelajaran bercorak one-size-fits all alias hanya satu pendekatan untuk kebutuhan yang berbeda-beda.
Di sinilah letak tantangannya. Untuk guru yang harus mendampingi siswa dalam jumlah banyak, jelas tak mudah untuk mengidentifikasi lalu melayani kebutuhan belajar setiap anak. Karena itu, berbeda dengan di atas kertas, pertanyaan apakah pendidikan saat ini sudah mengakomodasi keunikan dan potensi setiap anak, tidak begitu mudah dijawab di lapangan. Secara umum, sekurang-kurangnya ada empat prasyarat dasar untuk memastikan pembelajaran berdiferensiasi benar-benar berjalan. Pertama, proporsionalitas rasio guru-siswa. Kedua, pemahaman komprehensif guru mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Ketiga, kreativitas guru dalam memfasilitasi pembelajaran terutama untuk menyiasati beragam tantangan di lapangan. Keempat, kesediaan guru untuk belajar terus-menerus, atau dalam bahasa Kurikulum Merdeka, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tanpa variabel-variabel tersebut, ikhtiar menjalankan pembelajaran yang melayani keberagaman kondisi setiap anak tidak mungkin terwujud. Tentu masih banyak prasyarat lain yang dibutuhkan sesuai konteks setiap sekolah.
Berpusat pada muridAspek lain dari Kurikulum Merdeka yang juga perlu diangkat untuk menjawab pertanyaan sejauh mana anak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan misi memutus mata rantai gaya pembelajaran konvensional-tradisional yang cenderung searah dan indoktrinatif, pembelajaran jenis ini menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran, di dalam dan di luar kelas. Dalam pembelajaran model inilah, anak diarahkan untuk secara aktif terlibat dalam banyak hal, termasuk dalam mengambil keputusan. Dalam penentuan masalah yang akan digarap dalam proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), misalnya, anak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri masalah yang diangkat lengkap dengan alasan-alasan yang melatarinya. Demikian halnya dalam pembelajaran di kelas. Dengan materi pembelajaran yang sudah dikontekstualisasi sedemikian rupa oleh guru, anak distimulasi untuk mengekspresikan seluruh potensi dirinya hingga bermuara pada terciptanya anak yang bisa berpikir secara kritis dan mandiri; anak yang tidak hanya diam dan mengangguk di kelas. Baca juga: Mencegah Kegagalan Kurikulum Merdeka Itu hanya secuil contoh yang mewakili lapangnya ruang dalam Kurikulum Merdeka untuk membentuk anak yang bisa berpikir dan mengekspresikan diri. Dari ruang-ruang tersebut diharapkan pendidikan tidak lagi memproduksi anak yang hanya bisa meniru apa yang dikatakan guru, atau hanya bisa menulis ulang yang tertulis dalam buku. Tantangan yang sering terjadi di lapangan adalah, ada guru yang menerjemahkan pembelajaran yang berpusat pada murid melulu sebagai pembelajaran berbasis diskusi kelompok. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman guru atau pun demi alasan efektivitas. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Sekilas, ini terlihat masuk akal karena pengandaiannya dalam kelompok kecil, anak bisa lebih punya banyak kesempatan untuk terlibat secara aktif. Namun, di sisi lain, tanpa pendampingan yang intensif, keunikan setiap anak bisa tenggelam dalam kelompok. Tak mustahil anak yang kurang mampu secara akademik bisa berlindung di balik temannya yang lebih mampu. Bisa juga anak yang lebih mampu mendominasi sehingga yang kurang mampu terdesak semakin kerdil. Jika demikian, maka pembelajaran model diferensiasi dan berpusat pada murid gagal secara bersamaan.
Mendewasakan anakKembali kepada dua pertanyaan tadi, secara teori, tercetak jelas bahwa Kurikulum Merdeka menjamin terakomodasinya seluruh potensi dan keunikan setiap anak sebagaimana ia juga menggaransi terbentuknya kesanggupan bernalar dan mengekspresikan diri setiap anak. Namun, seperti banyak terjadi pada hal lain, dunia gagasan tidak selamanya ekuivalen dengan dunia lapangan. Beberapa catatan di atas tentu hanya seujung kuku dari kompleksnya tantangan yang ada di lapangan. Perlu ada sistem evaluasi yang terus-menerus agar gagasan besar Kurikulum Merdeka benar-benar berdampak, tidak sekadar menjadi legasi yang menandai jabatan seorang Mendikbudristek. Persoalan jomplangnya rasio guru-siswa tak boleh dibiarkan berlarut. Jika saja kita berhasil menata rasio seturut standar rasio internasional yakni 20-21 siswa per guru, jelas upaya untuk memfasilitasi keberagaman karakteristik anak bukan sekadar cita-cita kosong. Tentu saat bersamaan upaya meng-upgrade pemahaman dan keterampilan guru menjadi keharusan. Ruang-ruang latihan bernalar dan memformulasikan pikiran dengan alur yang tertata juga perlu diperbanyak. Ruang-ruang itulah yang pada akhirnya membantu anak bisa memetakan apa kebutuhannya, apa argumentasi dan data di baliknya, dan bagaimana mengurutkannya berdasarkan skala prioritas. Dengan begitu, aspirasinya murni lahir dari anak sendiri, bukan replikasi ide orang dewasa. Dengan begitu pula, kebutuhan anak tidak mudah dipelintir oleh kepentingan orang dewasa. Itulah kurikulum yang mendewasakan anak. Heribertus Jani, Fasilitator Sekolah Penggerak Provinsi DKI Jakarta; Peneliti Pusat Studi Kebangsaan Indonesia Universitas Prasetiya Mulya
ARSIP LINKEDIN Heribertus Jani Editor:
YOVITA ARIKA
|
| Kembali ke sebelumnya |