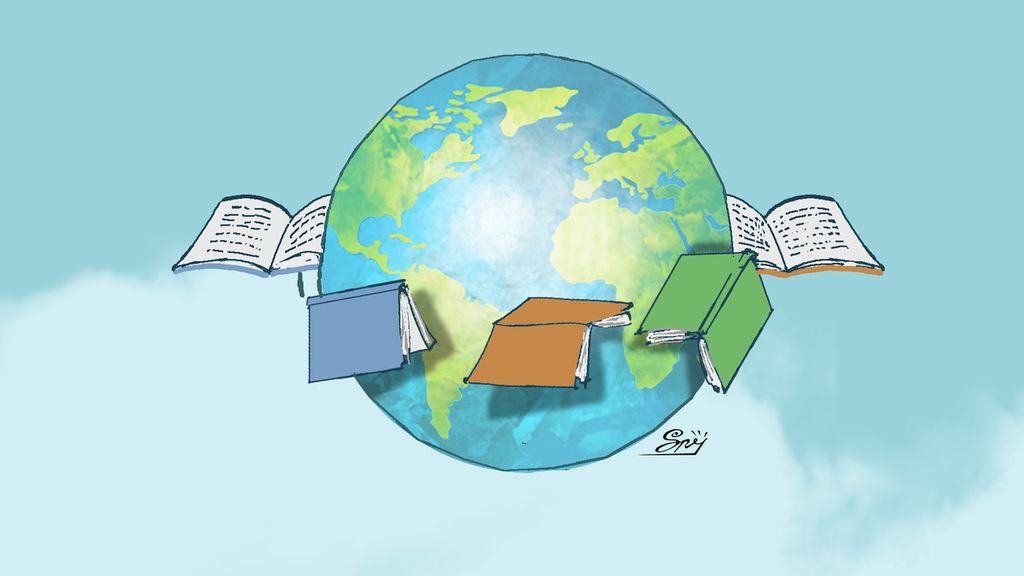Koleksi Perpustakaan DPR RI
| Judul | KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI: Simulakra Perguruan Tinggi |
| Tanggal | 11 Januari 2024 |
| Surat Kabar | Kompas |
| Halaman | - |
| Kata Kunci | Pendidikan Tinggi - Simulakra |
| AKD |
- Komisi X |
| Isi Artikel | Selama kebijakan pendidikan tinggi dibangun dengan model tirani matriks, perguruan tinggi akan hidup dalam simulakra. Oleh:
TAUFIQURRAHMAN
SUPRIYANTO Ilustrasi Pada 1981, seorang filsuf Perancis, Jean Baudrillard, menulis sebuah buku berjudul Simulacres et Simulation. Dalam buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada 1983 itu, Baudrillard memperkenalkan konsep ‘simulakra’ yang secara sederhana berarti silang-sengkarut tanda yang tak memiliki hubungan dengan kenyataan. Di dalam dunia yang dipenuhi oleh silang-sengkarut tanda semacam itu, kita sulit membedakan antara yang asli dan palsu. Segalanya menjadi kabur. Dahulu Baudrillard mencontohkan fenomena simulakra hanya ada pada televisi, film, iklan, dan budaya konsumerisme. Namun, kini simulakra tampaknya juga sudah mulai ada di perguruan tinggi, terutama di negara kita. Label kosong
Sejak 2020, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) menetapkan delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, yaitu (1) kesiapan kerja lulusan, (2) kegiatan mahasiswa di luar program studi, (3) kegiatan dosen di luar kampus, (4) praktisi mengajar, (5) rekognisi internasional untuk karya para dosen, (6) kerja sama internasional, (7) pembelajaran kolaboratif dan partisipatif, dan (8) akreditasi internasional. Sebuah perguruan tinggi akan dinilai bagus jika bisa memenuhi semua indikator tersebut. Merespons keputusan itu, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia berlomba-lomba untuk memenuhi IKU. Para pengelola perguruan tinggi beradu gengsi agar kampusnya menjadi yang terbaik dalam hal pemenuhan indikator kinerja. Pada saat yang sama mereka juga khawatir akan dicap memiliki kinerja buruk jika tidak berhasil memenuhi indikator tersebut. Dengan demikian, penetapan IKU ini menjadi momok baru bagi para pengelola perguruan tinggi. Baca Juga: Pendidikan Tinggi yang Kita Dambakan Tujuan penetapan IKU itu tentu saja sangat baik, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Namun, seperti yang sudah-sudah, pemerintah kita terkadang hanya terobsesi pada hasilnya, tetapi tidak mau memikirkan prosesnya. Kita bisa coba secara spesifik bahas IKU 5 dan 8, yaitu rekognisi internasional dan akreditasi internasional. Target IKU 5 dan 8 itu masuk akal hanya jika kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi sudah sangat memadai. Namun, jika kualitas sumber daya manusianya masih biasa-biasa saja atau bahkan di bawah rata-rata, pemberian target semacam itu justru akan menciptakan masalah baru. Untuk mendapatkan rekognisi internasional, misalnya, para dosen, antara lain, harus memiliki publikasi internasional.
Tentang publikasi internasional, pemerintah sudah membuat ketetapan lebih awal melalui Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Para dosen dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor wajib menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi agar bisa berhak mendapatkan tunjangan profesi. Dengan kebijakan seperti itu, jumlah publikasi akademisi Indonesia memang terbukti naik drastis. Berdasarkan data dari Scimago Journal & Country Rank, pada 2015, luaran ilmiah yang dihasilkan oleh akademisi Indonesia hanya 8.624 dokumen. Namun, pada 2020, angka tersebut naik sekitar 600 persen menjadi 51.721 dokumen. Namun, bisa jadi itu hanyalah capaian semu jika kita melihat temuan Macháček dan Srholec (2022) yang menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara paling banyak kedua setelah Kazakhstan dalam menyumbang artikel di jurnal-jurnal yang terindikasi predator selama rentang tahun 2015-2017. Asumsi bahwa itu semua hanyalah capaian semu semakin diperkuat oleh hasil investigasi Kompas beberapa bulan lalu yang menemukan adanya praktik perjokian dalam publikasi ilmiah sejumlah akademisi di Indonesia.
Itu semua menunjukkan bahwa target publikasi internasional memang tercapai, tetapi tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Bahkan, target-target yang tidak sesuai dengan kondisi sumber daya manusia yang tersedia justru melahirkan sejumlah praktik kotor yang menodai martabat perguruan tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada target akreditasi internasional. Untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional, sebuah perguruan tinggi tentu harus memenuhi standar-standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga pengakreditasi. Padahal, pada praktiknya, apa yang riil terjadi selama ini di beberapa perguruan tinggi belum memenuhi standar tersebut. Akhirnya, yang terjadi adalah fabrikasi data. Hal tersebut sangat bisa dipahami. Ibaratnya: sumber daya manusia yang tersedia masih level kecamatan, tetapi pemerintah meminta mereka bekerja dengan standar internasional. Akhirnya, muncullah simulakra itu. Kampus-kampus berbangga dengan segenap label-label internasional, tetapi sebenarnya label itu sama sekali tidak punya pijakan di kenyataan. Kualitas pendidikan tinggi kita secara umum masih terbelakang.
Akar masalah Simulakra perguruan tinggi seperti yang digambarkan di atas itu jelas masalah. Kita mesti berhenti mengejar dan berbangga dengan label-label kosong semacam itu. Akan tetapi, kita juga tidak bisa melokalisasi akar masalah ini hanya pada persoalan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Ada masalah struktural yang dapat menjelaskan mengapa kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi ini tidak dapat dipacu dengan menggunakan standar internasional. Hal yang paling mendasar tentu adalah sistem remunerasi dosen yang sungguh tidak wajar. Dalam sektor pendidikan, juga berlaku hukum berikut: ”if you pay peanuts, you get monkeys”. Jika Anda memberikan gaji rendah, jangan pernah berharap akan mendapatkan pekerja yang bagus. Dan hal ini terbukti baru-baru ini: formasi ASN dosen dengan kualifikasi S-3 banyak yang kosong. Sumber daya manusia Indonesia yang unggul sudah mulai berpikir ribuan kali untuk memilih bekerja sebagai dosen jika gaji pokoknya ternyata sangat rendah. Mereka lebih memilih bekerja di sektor industri atau berkarier di kampus luar negeri. Dengan demikian, jika pemerintah memang serius ingin membuat perguruan tinggi di Indonesia ini bertaraf internasional, yang pertama-tama perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi. Untuk itu, syarat niscayanya, meskipun belum tentu jadi syarat memadainya, adalah kenaikan gaji.
Selain masalah remunerasi, hal yang juga turut memperburuk kualitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi adalah apa yang Jerry Z Muller (2018) sebut sebagai ‘tirani matriks’. Ia adalah obsesi institusi untuk mengukur performa manusia berdasarkan angka-angka. Menurut Muller, obsesi ini juga dialami oleh institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Institusi pendidikan tinggi ini selalu mengukur performa dirinya dan manusia yang bekerja di dalamnya dengan matriks numerik: berapa banyak mahasiswa yang diterima, berapa banyak kehadiran mahasiswa di kelas, berapa banyak mahasiswa yang menang lomba, berapa banyak lulusan yang diterima kerja, berapa banyak publikasi internasional dosen, berapa banyak sitasi karya dosen, ranking berapa kampus kita tahun ini, dan lain sebagainya.
Mengukur performa kerja manusia dengan angka memang cara paling mudah. Akan tetapi, ia memiliki sejumlah konsekuensi yang sangat buruk bagi institusi itu sendiri. Di antaranya adalah perubahan tujuan pada apa yang sekadar dapat dihitung (Muller, 2018: 168). Tujuan utama publikasi ilmiah, misalnya, adalah untuk diseminasi pengetahuan dan kontribusi untuk bidang ilmu tertentu. Akan tetapi, karena nilai publikasi para akademisi diukur secara numerik, mereka berlomba-lomba melakukan publikasi hanya untuk menaikkan jumlahnya, tanpa memikirkan seberapa signifikan kontribusi keilmuannya. Akhirnya, publikasi ilmiah para akademisi di Indonesia hanya indah dalam angka, tetapi buruk dalam kenyataannya. Pergeseran tujuan itu juga akan membuat skala prioritas institusi menjadi terbolak-balik. Hal yang tidak substansial menjadi prioritas utama semata karena ia dapat dikuantifikasi dan mudah dipamerkan. Sementara hal yang substansial tidak pernah menjadi prioritas utama karena sering kali yang substansial itu tidak dapat dikuantifikasi. Baca Juga: Dari Terburuk Kedua Menjadi yang Terbaik Konsekuensi lain dari tirani matriks adalah tuntutan dokumentasi dan administrasi yang semakin tinggi (Muller, 2018: 18). Karena performa dosen diukur menggunakan matriks numerik, mereka akan disibukkan dengan penyusunan laporan kinerjanya. Semua kegiatan yang pernah mereka lakukan harus terdokumentasikan dengan baik agar terhitung sebagai pekerjaan yang layak diberi insentif. Tuntutan administrasi semacam itu tentu akan menyita sebagian waktu dan energi mereka yang seharusnya digunakan untuk membaca, menulis, dan meriset. Penetapan 8 IKU perguruan tinggi oleh Mendikbudristek itu merupakan contoh nyata tirani matriks yang disebutkan Muller. Selama kebijakan pendidikan tinggi masih dibangun dengan model tirani matriks semacam itu dan tanpa disertai upaya serius peningkatan sumber daya manusianya, maka selama itu pula perguruan tinggi kita akan hidup dalam simulakra. Taufiqurrahman, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan Direktur Antinomi Institute
DOK. PRIBADI Taufiqurrahman Editor: YOVITA ARIKA
|
| Kembali ke sebelumnya |