 KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO
KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO
KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO
Petani membawa pesan dan harapan sebelum menggelar upacara bendera merayakan HUT ke-75 Republik Indonesia di areal persawahan di Grumbul Kalibacin, Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (17/8/2020).
Ketahanan pangan Indonesia, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index/GFSI), cenderung membaik lima tahun terakhir. Skornya bertambah dari 50,7 pada 2015, lalu 53,2 tahun 2017, dan 62,6 pada 2019. Peringkat Indonesia juga terus naik dari 75 (2015), lalu 68 (2017), dan 62 dari 113 negara pada 2019.
Indeks diukur dengan melihat aspek affordability atau kemampuan konsumen untuk membeli makanan; availability atau kecukupan pasokan pangan nasional, risiko gangguan pasokan, kapasitas negara mendistribusikan pangan, dan penelitian untuk memperluas hasil pertanian; serta quality and safe yang menyangkut kualitas dan keamanan pangan.
Akan tetapi, penilaian itu mengabaikan sumber pangan, tidak peduli apakah bahan pangan diproduksi oleh petani di dalam negeri atau didatangkan melalui importasi. Oleh karena itu, tidak heran jika Singapura berada di peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2019 meski memiliki segenap keterbatasan sumber daya pertanian.
Bagi Indonesia, kenaikan indeks itu bisa jadi menggambarkan perbaikan daya beli, distribusi barang, atau kualitas pangan. Namun, apakah petani Tanah Air semakin sejahtera hidupnya? Apakah mata pencariannya sebagai produsen pangan masih menjanjikan di masa depan?
Sayangnya, sejumlah data menyajikan fakta yang kurang menggembirakan. Angka nilai tukar petani (NTP), salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan petani, misalnya, cenderung menurun dalam dua dekade terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, meski berfluktuasi, NTP cenderung turun dari 119,38 tahun 2000 menjadi 103,21 pada 2019.
 KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Personel SAR mengemas sayuran untuk dibagikan kepada warga secara gratis di Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2020). Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi selama pandemi, kegiatan itu juga untuk membantu perekonomian petani sayur yang harga hasil panennya anjlok.
NTP dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. NTP di atas 100 berarti petani mengalami surplus karena harga produksinya lebih besar dibandingkan dengan harga konsumsinya. Dengan mengacu data itu, kesejahteraan petani cenderung turun dalam dua dekade terakhir.
Penyusutan luas lahan pertanian juga sejalan dengan penurunan kesejahteraan petani. Luas baku sawah nasional, sesuai dengan data yang diumumkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Wilayah, BPS, serta Kementerian Pertanian, Selasa (4/2/2020), mencapai 7,465 juta hektar, turun dibandingkan dengan luas baku sawah tahun 2013 yang 7,75 juta hektar. Artinya, ada 285.000 hektar lahan pertanian yang beralih fungsi selama kurun waktu 2013-2019 atau rata-rata terjadi penyusutan 47.500 hektar lahan sawah per tahun.
Baca juga: Insentif yang Hakiki bagi Petani
Jumlah rumah tangga pertanian juga berkurang meski situasi ini tidak semata menggambarkan penurunan sektoral. Jumlah rumah tangga tani, menurut Survei Pertanian Antar Sensus 2018, mencapai 27,2 juta rumah tangga. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan data dari Sensus Pertanian 2003 yang tercatat 31,2 juta rumah tangga.
Segenap situasi menggambarkan bahwa sektor ini makin ”dijauhi” karena dianggap kurang menguntungkan dan serba tidak pasti. Laporan Kompas dalam beberapa tahun terakhir menyajikan fakta bahwa petani dan buruh tani masih menghadapi tekanan di hulu ataupun di hilir. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mendongkrak produksi dan penghasilan, tetapi kerap terguncang oleh perubahan cuaca, serangan hama penyakit, atau tekanan pasar.
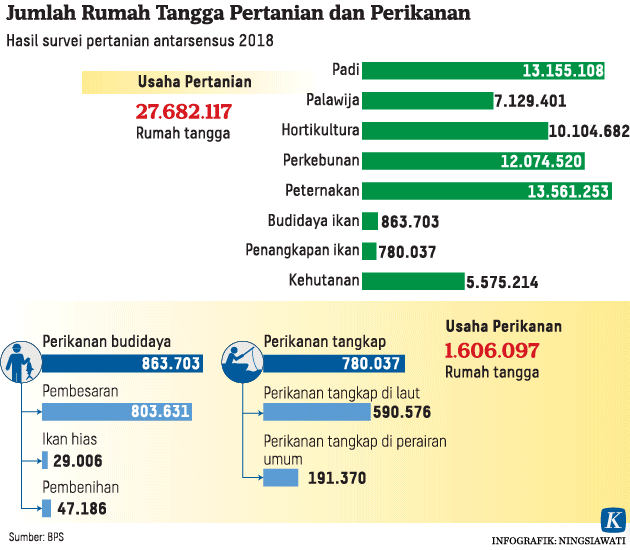
Ada sederet problem yang hingga kini belum mendapatkan solusi. Masalah itu di antaranya soal skala usaha, terutama terkait luas lahan garapan dan produktivitas tanaman, yang belum ekonomis; situasi cuaca yang makin tidak menentu; sejumlah bantuan dan subsidi pemerintah yang belum efektif atau belum tepat sasaran; serta harga jual hasil panen yang fluktuatif.
Soal lahan, data Sensus Pertanian 2003 dan 2013 menunjukkan, 508.000 hektar lahan pertanian di Pulau Jawa beralih kepemilikan dari rumah tangga petani ke nonpetani. Alih kepemilikan terbesar, yakni 204.318 hektar (40 persen), terjadi di lahan seluas kurang dari 0,1 hektar yang selama ini menjadi sumber pencarian petani gurem. Ketimpangan penguasaan lahan juga menjadi problem. Sebanyak 56 persen rumah tangga tani menguasai 13,3 persen lahan atau luas kepemilikan rata-rata kurang dari 0,5 hektar.
Petani belum berdaulat atas harga hasil jerih payahnya.
Petani juga belum berdaulat atas harga hasil jerih payahnya. Unjuk rasa peternak ayam, petani tebu, dan petambak garam memprotes harga yang anjlok setahun terakhir mengindikasikan para produsen pangan ini tidak berdaya menghadapi tekanan pasar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebenarnya mengamanatkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen demi melindungi pendapatan dan daya beli petani. Namun, pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan harapan.
Faktor terakhir ini yang melemahkan motivasi petani sehingga mereka terpaksa pasrah, beralih ke tanaman lain, atau menempuh jalan frustrasi: keluar dari sektor pertanian. Ketika demikian, apa artinya kenaikan indeks ketahanan pangan, sementara para produsen pangan di dalam negeri justru makin kerap tertekan?