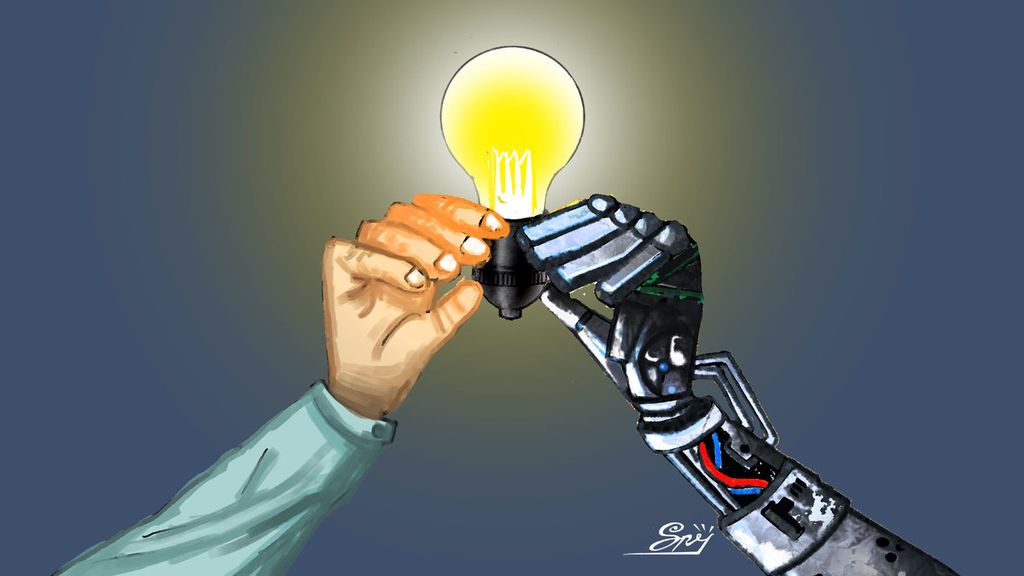
Pendidikan tinggi harus melakukan reposisi strategis dalam mengadopsi new IT agar tetap relevan. Misalnya, memikirkan cara memosisikan new IT sebagai alat melakukan transfer nilai/kebijaksanaan, tak sekadar pengetahuan.
Dunia sudah berubah, dan tak ada jalan untuk kembali. Editorial MIT Technology Review (Mei 2023) menyebutkan, traditional IT (sering disebut sebagai information technology) mulai digantikan new IT atau intelligent transformation.
New IT yang memungkinkan terjadinya transformasi digital ini berbasis lima elemen kunci, yaitu perangkat pintar (smart devices), komputasi tepi (edge computing), komputasi awan (cloud computing), jaringan berkecepatan tinggi, 5G (high-speed networks), dan kecerdasan buatan (artificial intelligent/AI).
Arsitektur teknologi informasi baru ini menciptakan peluang nyaris tak terbatas. Paradigma teknologi ini mendorong laju inovasi dan produktivitas, memberi energi pada pengembangan AI, merevolusi cara perusahaan atau organisasi menggunakan data, dan mendukung kelincahan bisnis. Fenomena ini terjadi di semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga apa yang ingin didiskusikan dalam artikel ini, yaitu pendidikan (khususnya pendidikan tinggi).
Arsitektur teknologi informasi baru ini menciptakan peluang nyaris tak terbatas.
Namun, perubahan juga memunculkan problem tersendiri, terutama terkait cara merespons berikut implikasi etik yang dibawanya. Dalam konteks pendidikan (tinggi), elemen new IT yang paling banyak memantik perdebatan sekaligus kecemasan adalah AI, yang beberapa bulan ini seolah terepresentasi oleh kehadiran ChatGPT. Harus diakui, respons awal terhadap ChatGPT di dunia pendidikan tinggi adalah kepanikan.
Kecerdasan buatan ini dikhawatirkan membawa dampak serius, terutama terkait etika (kecurangan, plagiarisme), posisi dosen, atau kurikulum. Reaksi panik ini terbaca, misalnya, dari larangan penggunaan ChatGPT di kalangan perguruan tinggi di AS ataupun Indonesia.
Persoalannya, sudah tepatkah reaksi tersebut? Apakah kepanikan terhadap teknologi akan membuat pendidikan tinggi tetap relevan? Penulis ingin membuka diskusi ini dengan bertitik tolak pada kenyataan bahwa kita tak bisa menolak teknologi. Meski ditaburi kritik, jutaan orang (termasuk mahasiswa) sudah bermain-main dengan AI atau ChatGPT. Dalam waktu tak terlalu lama, semua orang di planet ini akan mengetahui dan menggunakannya.
Perkembangan AI sudah tiba pada fase point of no return.
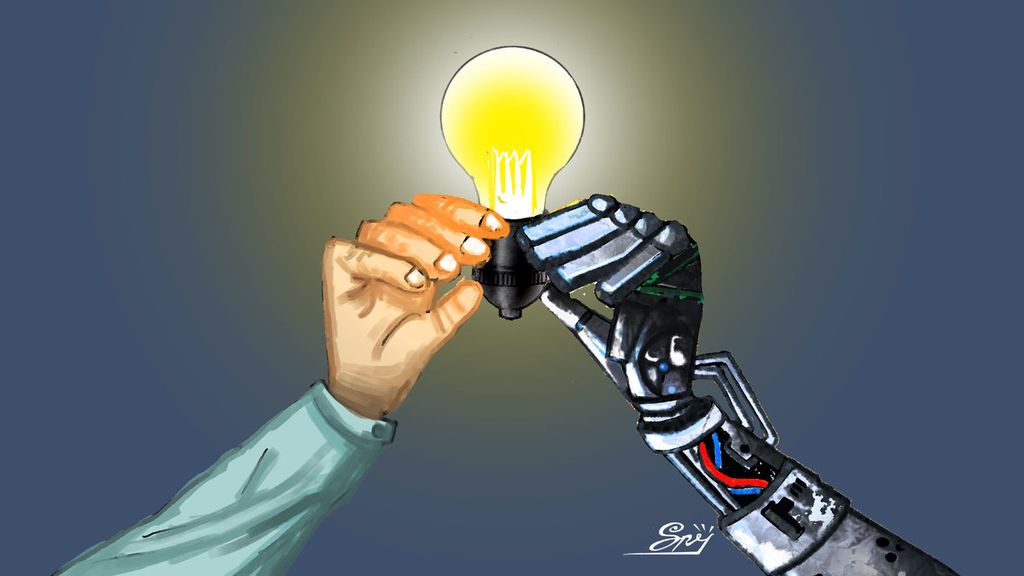
Poin krusialnya terletak pada bagaimana akademisi menemukan cara merespons disrupsi new IT ini, misalnya dengan memikirkan penyesuaian kurikulum berikut metode pembelajarannya. Yang perlu dipahami, tahun-tahun mendatang tidak lagi ditentukan oleh seberapa cepat kita mengadopsi digital, tetapi oleh cara kita mentransformasi konten digital menjadi sesuatu yang lebih relevan.
Respons pendidikan tinggi terhadap AI (ChatGPT) ini perlu didiskusikan secara serius. Apalagi, teknologi ini terus berkembang. OpenAI kabarnya menyiapkan versi GPT-4, sedangkan Microsoft dan Google sudah meluncurkan Bing Chat dan Bard.
Yang harus dipahami terkait new IT seperti ChatGPT ini adalah bahwa kecurangan bukanlah problem baru di dunia pendidikan. Jauh sebelum ini sudah muncul problem terkait kalkulator di dunia pendidikan, disusul Google, Wikipedia, dan lainnya. Namun, dunia pendidikan tinggi bisa sintas.
Hari ini pun pasti banyak mahasiswa menggunakan ChatGPT. Tetapi apakah solusinya harus melarang penggunaan ChatGPT, sebagaimana dulu pernah terpikir melarang penggunaan kalkulator, Google, atau Wikipedia?
Di sinilah akademisi perlu melakukan eksperimen terkait adopsi AI di dalam pendidikan tinggi. Dukungan pemerintah sudah pasti dibutuhkan, terutama dalam bentuk dana, pelatihan, ataupun regulasi untuk memastikan kehadiran AI tidak akan menjadi akhir dari pendidikan, tetapi justru awal dari pendidikan baru.
Yang harus dipahami terkait new IT seperti ChatGPT ini adalah bahwa kecurangan bukanlah problem baru di dunia pendidikan
Yang perlu dilakukan para pemangku kepentingan pendidikan tinggi adalah mengubah sikap terhadap new IT seperti ChatGPT ini. Maka, yang diperlukan sekarang ini adalah semacam new education.
Di AS, kembali merujuk laporan MIT Technological Review (Mei 2023), banyak sekolah atau universitas mulai mengintegrasikan mesin AI seperti ChatGPT ke dalam pembelajaran.
Universitas Harvard bahkan dikabarkan akan menggunakan AI Professor untuk mengajar mahasiswa. Pendidik mulai berpikir AI seperti ChatGPT dapat digunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih baik.
Chatbot canggih tersebut bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu yang membuat pembelajaran lebih interaktif, dan menjadi pengubah permainan (game changer) yang memberi dampak besar terhadap dunia pendidikan.
Pendidikan tinggi sudah tidak mungkin lagi menolak AI, apalagi bisnis dan industri pasti menggunakannya untuk efisiensi dan akurasi layanan. Artinya, mahasiswa akan berkarier di lingkungan yang kaya AI (AI rich-environment). Mereka akan diminta menggunakan teknologi ini agar dapat bekerja efektif.

Ilustrasi
Karena itu, pendidik wajib memastikan peserta didik memiliki pengalaman dengan teknologi ini, serta mengembangkan praktik yang efektif untuk penggunaan yang optimal.
Bahwa ChatGPT akan juga digunakan untuk menyontek, itu juga pasti. Namun, membuang teknologi ini dari ruang kelas (daripada mencoba memanfaatkannya) rasanya seperti tindakan picik.
Bagaimanapun AI pasti akan sampai ke ruang kelas. Tugas pendidik adalah memastikannya untuk digunakan secara benar.
Ada satu kelemahan mesin AI seperti ChatGPT ini. Meski dapat menyajikan jawaban cepat dan mudah untuk beragam pertanyaan, alat ini tidak membangun kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah; keterampilan yang sangat penting untuk kesuksesan akademis dan hidup. Sejumlah pendidik di AS pernah melakukan eksperimen penggunaan ChatGPT untuk mengajarkan berpikir kritis dan pemecahan masalah di dalam kelas.
Mesin ini ternyata bisa dimanfaatkan di dalam kelas. Namun, di sisi lain, jawaban ChatGPT juga sering tidak akurat dan bias. Maka yang dilakukan pendidik adalah menunjukkan tidak hanya cara menemukan jawaban melalui ChatGPT, tetapi juga mana informasi yang bisa dipercaya dan mana yang tidak, serta cara membedakannya.
Meski dapat menyajikan jawaban cepat dan mudah untuk beragam pertanyaan, alat ini tidak membangun kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah; keterampilan yang sangat penting untuk kesuksesan akademis dan hidup.
Kekurangan, bias, atau ketidakakurasian jawaban bisa menjadi titik awal diskusi membangun kritisisme di dalam kelas. Dengan kata lain, pendidik tidak lagi berperan sebagai penjaga gerbang informasi, tetapi fasilitator.
Jika digunakan dengan benar, new IT ini justru bisa membawa lebih banyak interaktivitas di dalam kelas. Metode pembelajaran yang membuat peserta didik kreatif, bermain peran, atau berpikir kritis akan menghasilkan pembelajaran lebih mendalam daripada hafalan.
Sampai hari ini, pengaruh ChatGPT terhadap dunia akademis memang belum sepenuhnya dipahami. Namun, alih-alih menolak new IT, akademisi sebaiknya memikirkan cara merespons dan mengadaptasinya agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau menyelesaikan masalah dengan memanfaatkannya.
Pendidikan tinggi harus melakukan reposisi strategis dalam mengadopsinya agar tetap relevan. Misalnya, memikirkan cara memosisikan new IT sebagai alat melakukan transfer nilai/kebijaksanaan, tidak sekadar sebagai alat transfer pengetahuan.
Harus diingat, dunia telah menjadi global brain dengan menjamurnya beragam learning channel. Pengetahuan bisa diperoleh di mana-mana dengan mudah tanpa harus belajar di kampus meski kampus mungkin bisa membuat pengetahuan lebih terstruktur. Namun, peran transfer nilai dan kebijaksanaan hidup (life skill) dengan bantuan new IT menjadi lebih penting. Jika peran ini dijalankan, niscaya pendidikan tinggi akan tetap menjadi relevan.
Benny LiantoRektor Universitas Surabaya
Editor: SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN